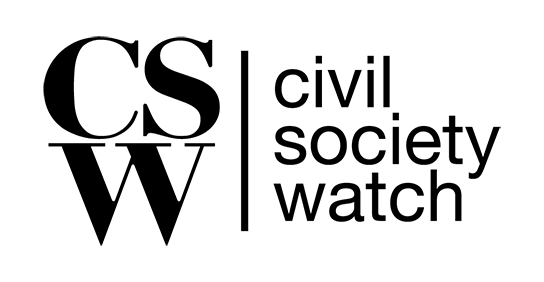Jakarta, CSW – Isu kekerasan seksual, khususnya terhadap kaum perempuan, kini sedang ramai menjadi bahan berita di media massa. Namun, ternyata kekerasan seksual ataupun nonseksual juga bisa terjadi pada jurnalis perempuan. Ini menjadi penting bagi CSW karena jurnalis perempuan bekerja di berbagai media, yang merupakan bagian dari civil society.
Terkait isu tersebut, pada Desember 2021 ini PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) dengan dukungan USAID dan Internews telah meluncurkan buku “Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia: Ancaman Bagi Jurnalisme dan Kebebasan Pers.”
Buku ini merupakan laporan penelitian (survei dan wawancara) yang dilakukan PR2Media pada Agustus-September 2021, yang diikuti forum diskusi terarah (FGD) dengan para pemangku kepentingan pada Oktober 2021.
Survei berskala nasional tersebut menemukan, dari 1.256 jurnalis perempuan yang menjadi responden, sebanyak 1.077 responden (85,7%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka, baik di ranah digital maupun ranah fisik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70,1% responden pernah mengalami kekerasan di ranah digital sekaligus di ranah fisik. Sebanyak 7,9% responden pernah mengalami kekerasan digital saja, dan 7,8% responden pernah mengalami kekerasan fisik saja. Hanya sebanyak 179 responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali.
Dari segala jenis kekerasan di ranah digital dan fisik, jenis yang paling banyak dialami oleh responden adalah komentar body shaming secara fisik (59%). Ini diikuti komentar mengganggu/melecehkan bersifat non-seksual secara daring (48%), komentar body shaming secara daring (45%),dan ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual (40%).
Lalu, ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual (37%), komentar mengganggu/melecehkan bersifat seksual secara daring (34%), diskriminasi gender di tempat kerja (32%), penyebaran misinformasi/fitnah secara daring (28%), penghinaan terkait suku/ agama/ras secara daring (22%), dan serangan fisik yang bersifat seksual (22%).
Pengiriman Foto Alat Vital
Berdasarkan 272 respons yang masuk (di luar sikap reponden yang mendiamkan), ada beberapa cara responden menanggapi kasus kekerasan yang dialami. Cara yang paling banyak dilakukan responden (52%) adalah melaporkan ke atasan atau rekan kerja. Cara yang juga cukup banyak adalah melaporkan ke organisasi terkait (29%) dan mengajukan tuntutan hukum (10%).
Respons lainnya adalah menyelesaikan masalah secara pribadi. Seperti: menghadapi sendiri, menegur, melakukan diskusi, melancarkan serangan balik, bercerita ke kerabat, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau artikel.
Dari 1.256 responden, usulan terbanyak terkait dukungan alat maupun bantuan yang dapat mencegah atau mengatasi kekerasan adalah pelatihan (40%), diikuti panduan atau modul mencegah dan mengatasi kekerasan (29%), pendampingan atau bantuan hukum (23%), dan pendampingan psikologis (7%).
Dalam wawancara, semua informan (enam jurnalis) mengatakan, mereka pernah mengalami kekerasan bersifat seksual yang dilakukan oleh narasumber, baik di ranah digital maupun fisik. Di ranah digital, para informan mengalami beragam bentuk kekerasan seksual. Seperti rayuan oleh narasumber yang disampaikan melalui WhatsApp, hingga pengiriman foto alat vital oleh narasumber.
Kekerasan seksual di ranah fisik, misalnya, dipegang-pegang rambutnya, pundaknya, dan pipinya, lalu dirangkul dan dipegang pantatnya, serta dipegang-pegang tangannya. Contoh lainnya, ajakan bertemu atau wawancara di hotel dan ajakan menikah untuk dijadikan istri kedua atau ketiga.
Jurnalis Perempuan Lebih Rentan
Untuk kekerasan non-seksual, para informan mengatakan, jenis kekerasan ini terjadi terutama karena liputan yang dikerjakan oleh informan dan dilakukan oleh narasumber. Kekerasan ini terjadi dalam ranah fisik maupun digital. Misalnya, tiga informan pernah menerima ancaman pembunuhan, yang disampaikan secara tatap muka maupun melalui telepon dan saluran media sosial.
Meskipun data survei tidak menunjukkan hubungan yang kuat antara tindak kekerasan dan topik liputan, wawancara menunjukkan, jurnalis perempuan lebih rentan terhadap kekerasan saat meliput isu-isu yang dianggap berisiko. Seperti: liputan isu lingkungan dan gender serta seksualitas (LGBTIQ).
Ini sejalan dengan pernyataan lembaga Committee to Protect Journalists, yang menggolongkan liputan investigasi lingkungan di negara-negara berkembang dalam kategori berbahaya, berada pada tingkat kedua setelah liputan konflik bersenjata.
Menjelang akhir 2021, kekerasan terhadap jurnalis perempuan mendapat perhatian lebih besar ketika Maria Ressa, jurnalis perempuan Filipina –yang mengalami rangkaian kasus kekerasan di era Presiden Rodrigo Duterte– menerima hadiah Nobel Perdamaian bersama jurnalis Rusia Dmitry Muratov. Kedua jurnalis ini berjuang dalam membela kebebasan berekspresi.
Maria Ressa, salah satu pendiri media daring Rappler, dinilai Komite Nobel menggunakan kebebasan berekspresi untuk “mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, dan meningkatnya autoritarianisme di negaranya.”
Sebagai salah satu jurnalis perempuan paling terkenal di dunia saat ini, Maria Ressa banyak diberitakan selama beberapa tahun terakhir, karena ia mengalami serangan digital yang terkoordinasi. Ia juga diserang dengan beragam tuntutan hukum, yang dinilai para pembela hak asasi sebagai serangan yang didukung oleh negara. #
(Satrio)